Pancasila Ibarat Payung Besar
Pancasila ibarat sebuah payung besar yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap keragaman di Indonesia. Keragaman suku, budaya dan agama mendapatkan tempat persemaiannya di bumi Pancasila yang memosisikan agama pada tempat terhormat.
Negara yang berdasarkan Pancasila, mengembalikan domain agama kepada pemeluknya, tetapi juga memberikan suasana yang kondusif bagi agama memberikan sumbangsih yang berharga bagi bangsa. Pancasila yang menjiwai UUD 45 menghadirkan kebijakan yang anti deskriminatif untuk semua.
Pancasila Sebagai Kompromi
Pancasila diterima sebagai sebuah kompromi politik karena Pancasila bermanfaat bagi semua agama-agama yang ada di Indonesia. Pancasila bukan hanya mengijinkan tetapi juga mendukung apa yang disebut bukan negara sekuler dan bukan negara agama yang mendasarinya pada agama tertentu.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah untuk mendorong agama memainkan peran yang penting di dalam urusan-urusan publik Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memainkan peran yang menentukan yang menjadi dasar keempat sila yang lain, yaitu sila kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial.Namun, tidak berarti Pancasila harus ditafsirkan secara vertikalisme, karena agama harus menghadirkan perikemanusiaan.
Namun, mengijinkan agama-agama untuk hadir dalam ruang publik bukan persoalan mudah bagi negara-negara sekuler yang melihat agama bukan sebagai kebutuhan, bahkan telah memarginalkannya begitu lama. Apalagi pemisahan mana yang menjadi domain privat dan domain publik itu sendiri tidaklah mudah. Agama-agama perlu secara bersama membangun konsensus bersama untuk menghadirkan etika bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai dari Pancasila.
Keyakinan bahwa agama dapat memberikan kontribusi penting bagi kehidupan bersama yang damai, merupakan pengalaman Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, agama-agama budaya Indonesia hingga saat ini masih dapat dijumpai dengan mudah.
Pancasila memosisikan agama pada tempat terhormat
Sebaliknya, agama-agama besar yang masuk ke Indonesia, tidak sedikit yang kemudian mewarnai agama-agama suku itu. Masuknya agama-agama besar ke Indonesia secara damai itulah yang membuat keragama Indonesia terawat dengan baik. Jadi, Indonesia tidak pernah mengalami kehidupan tanpa agama, atau negara sekuler yang meminggirkan peran agama.
Indonesia yang toleran juga tidak pernah menghadirkan agama negara yang mengatur kehidupan masyarakat secara ketat. Pelajaran dari banyak negara agama menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa negara-negara yang mengatur kehidupan masyarakatnya dengan nilai-nilai agama yang amat ketat juga tidak mampu mengatasi persoalan sosial seperti korupsi, kemiskinan dan keborobrokan birokrasi.
Finalitas jalan Pancasila
Dengan demikian jelaslah bahwa Indonesia telah berada dalam jalan yang benar, yakni menjadi bukan negara agama yang mendasari pada agama tertentu, demikian juga bukan negara sekuler yang meminggirkan peran agama. Tidak ada komunitas agama apapun yang secara jumawa bahwa mereka mempunyai jawaban untuk memajukan Indonesia. Tetapi, semua elemen bangsa di negeri ini perlu bersatu untuk mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan Indonesia. Secara khusus setelah negeri ini merayakan kemerdekaannya yang ke-75.
Sengkarut antara agama dan negara pada abad pertengahan masih menyisakan trauma dan ketakutan. Runtuhnya komunisme dan kembalinya sekularisme tetap membuat masyarakat berhati-hati saat membahas agama untuk menghindari masuk ke ranah privat terlalu dalam.
Negara-negara demokrasi kini menghadapi tantangan baru, karena sebagai negara demokrasi mereka harus mengijinkan agama-agama yang beragam itu hadir dalam ruang publik, disini hubungan antara agama dan negara memasuki fase yang baru.
Indonesia sebagai negara dengan banyak agama kini menghadapi persoalan yang tidak mudah seiring dengan kebangkitan agama-agama yang menuntut untuk hadir mendominasi ruang publik dengan alasan mayoritas. Padahal, Pancasila secara jelas telah mengingatkan bahwa Pancasila tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Satu untuk semua, semua untuk satu begitu dikatakan Presiden Soekarno.
Timbul pertanyaan apakah Pancasila masih mampu menjadi payung yang lebar untuk menjadi landasan etis bersama agama-agama yang kerap tergoda untuk menunjukkan hegemoninya pada ruang publik? Kita berharap kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia akan tetap pada pilihan, bahwa Pancasila telah Final sebagai landasan bersama seluruh rakyat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dr. Binsar Antoni Hutabarat
https://www.binsarhutabarat.com/2020/08/pancasila-ibarat-payung-besar.html


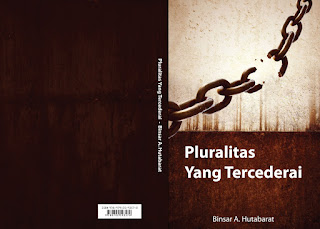




123.jpg)
